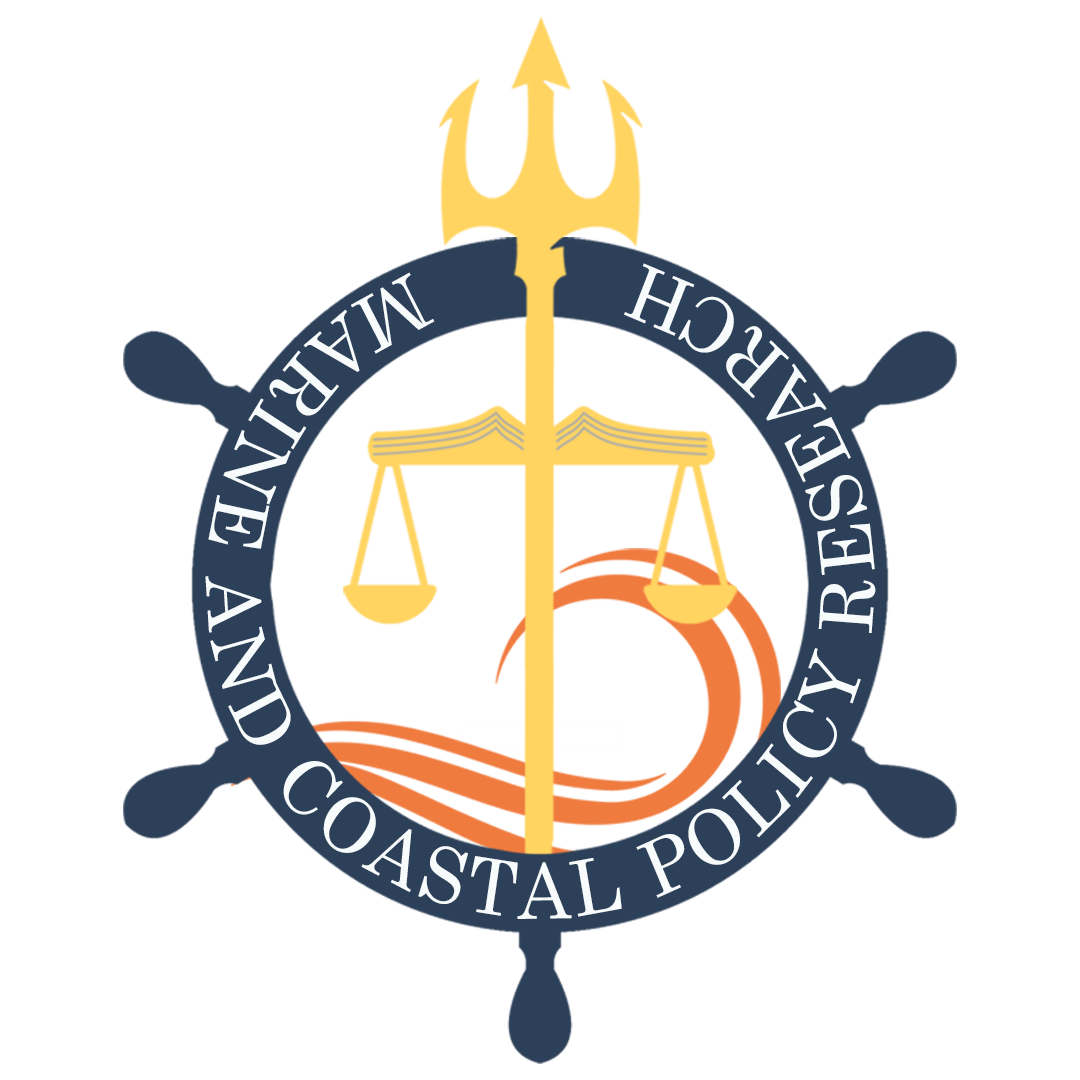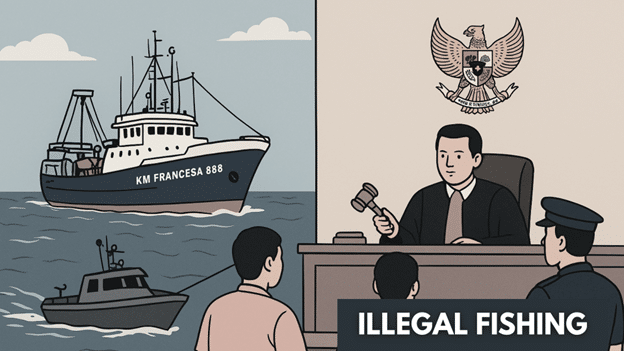Oleh : Bintang Azahra
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan kekayaan laut yang luar biasa. Terletak di wilayah Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle), perairan Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan dan sekitar 76% jenis terumbu karang dunia. Keanekaragaman hayati ini menjadikan Indonesia pusat perhatian global baik dari sisi ekologis maupun ekonomis. Namun, dibalik potensinya yang besar, ekosistem laut Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam kelestariannya.
Salah satu tantangan terbesar adalah praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing atau penangkapan ikan ilegal yang merusak habitat dan menurunkan stok ikan. Di samping itu, degradasi ekosistem pesisir, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, semakin memprihatinkan akibat aktivitas manusia, seperti reklamasi pantai, polusi limbah industri, hingga penangkapan ikan dengan bahan peledak. Masalah lain yang tak kalah serius adalah polusi laut, khususnya sampah plastik. Dengan perkiraan 3,2 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahunnya, Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah plastik di dunia. Selain itu, alih fungsi lahan pesisir untuk kepentingan industri dan pariwisata juga kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, yang semakin memperparah kondisi ekosistem laut.
Implementasi Kebijakan Pelestarian Laut
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis untuk melestarikan ekosistem laut. Salah satunya adalah penerapan Ekonomi Biru, sebuah kebijakan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui ekonomi biru, pemerintah mendorong pengembangan perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, dan pemulihan ekosistem kritis, seperti mangrove dan terumbu karang. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagai upaya melindungi keanekaragaman hayati laut. Hingga tahun 2024, Indonesia menargetkan 32,5 juta hektar kawasan laut sebagai kawasan lindung.
Di beberapa daerah, pemerintah mendorong penguatan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi konservasi. Contoh tradisi seperti Sasi Laut di Maluku dan Papua menunjukkan bagaimana masyarakat lokal secara turun-temurun telah mempraktekkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dalam tradisi ini, pemanfaatan laut diatur berdasarkan musim dan lokasi tertentu untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Langkah ini menunjukkan bahwa peran masyarakat lokal sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Selain itu, pemerintah juga memperketat penegakan hukum dengan melarang praktik-praktik merusak, seperti penggunaan cantrang dan memantau aktivitas perikanan melalui teknologi satelit untuk mencegah penangkapan ikan ilegal.
Meskipun kebijakan ini sudah berjalan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Pengawasan di wilayah laut Indonesia yang begitu luas masih terbatas, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri dalam mengontrol aktivitas ilegal di laut. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, seringkali tidak berjalan efektif, menghambat implementasi kebijakan. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut juga menambah beban dalam upaya konservasi ini.
Rekomendasi dan Langkah Strategis
Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis yang lebih efektif perlu segera diterapkan. Salah satu solusi adalah pemanfaatan teknologi modern, seperti pemantauan berbasis satelit dan drone, untuk mendeteksi kerusakan ekosistem dan aktivitas ilegal secara real-time. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar kesadaran lingkungan tumbuh sejak dini. Program edukasi berbasis sekolah dan komunitas menjadi kunci dalam membangun generasi yang peduli terhadap laut. Di sisi lain, kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional harus diperkuat untuk menangani masalah lintas batas, seperti IUU Fishing dan polusi laut. Upaya rehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti mangrove dan terumbu karang, juga harus menjadi prioritas dalam program konservasi nasional.
Dengan kebijakan yang lebih terstruktur, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam upaya konservasi laut. Keberhasilan ini tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Konservasi laut bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia.
#MCPRDailyNews