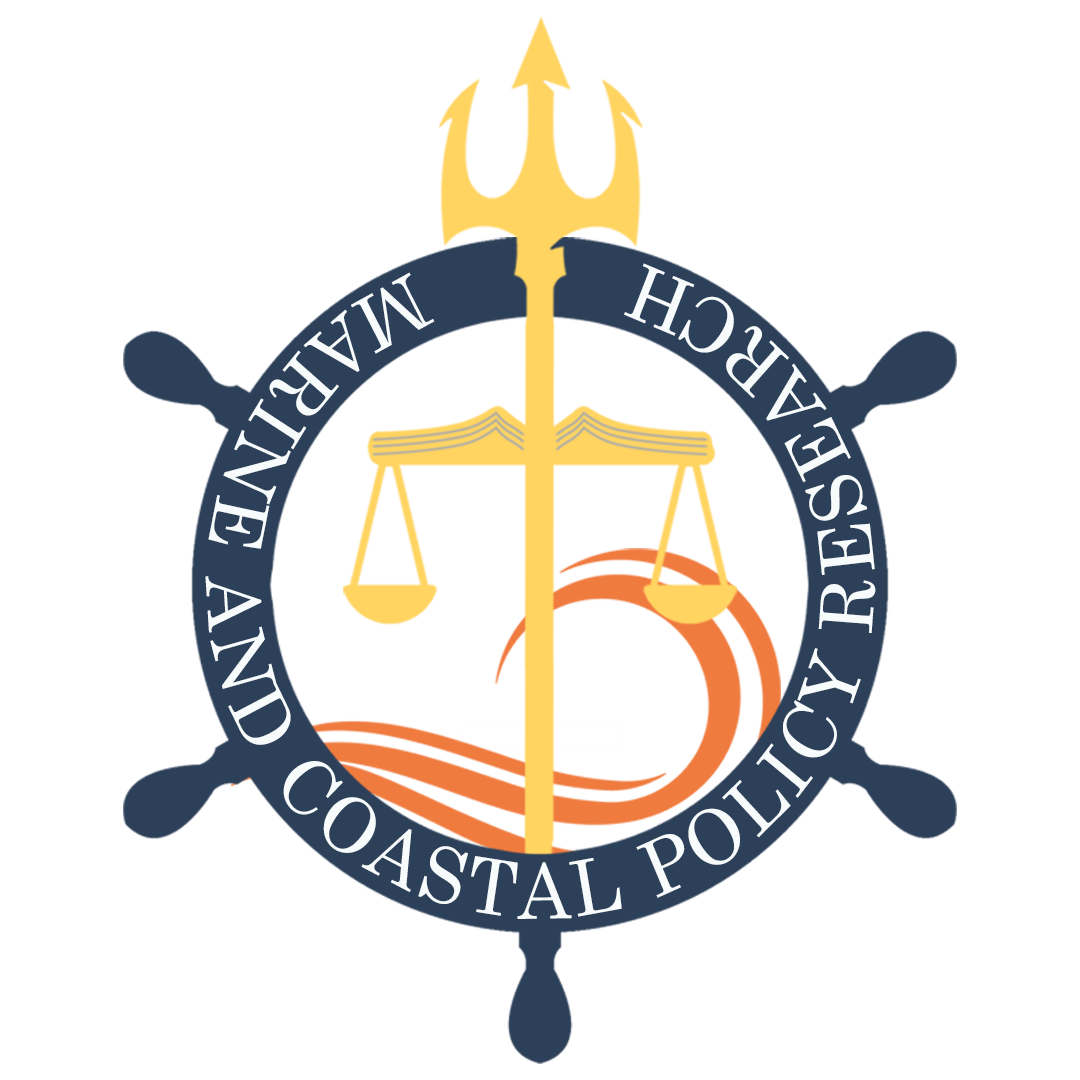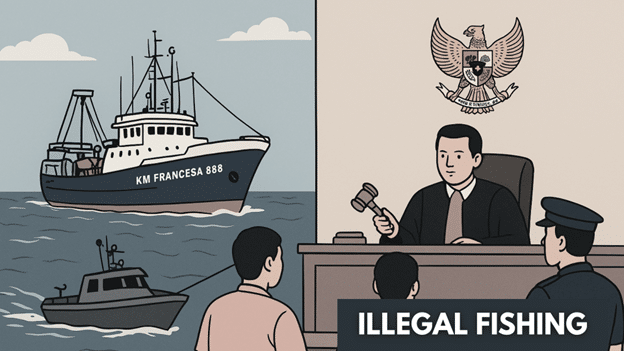Oleh : Muzhaffirah Gyda Kania Subagja
Sebagai masyarakat pesisir, Suku Bajo menjalin keterikatan yang kuat dan mendalam dengan ekosistem laut. Ketergantungan mereka terhadap laut tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial, budaya, hingga spiritual. Komunitas Bajo tersebar di berbagai kawasan pesisir di Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah total Suku Bajo mencapai 314.884 orang. Bagi Suku Bajo, laut bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Namun, Suku Bajo kini menghadapi tantangan besar. Pembangunan pesisir yang masif, perubahan iklim yang mengancam habitat alami, serta ketidakpastian hukum atas ruang hidup mereka membuat komunitas ini semakin rentan. Tanpa adanya perlindungan yang adil dan adaptif, identitas budaya dan masa depan Suku Bajo sebagai komunitas maritim asli Indonesia bisa terancam hilang.
Dalam menghadapi ancaman terhadap ruang hidup tradisional, Jepang melindungi komunitas pesisirnya melalui model Funaya di Desa Ine, Kyoto. Funaya merupakan rumah tradisional berbentuk panggung yang dibangun di atas air, berfungsi ganda sebagai tempat tinggal dan tempat penyimpanan perahu. Pemerintah Jepang menetapkan kawasan tersebut sebagai warisan budaya nasional, sekaligus menerapkan sistem zonasi eksklusif dan perlindungan berbasis hukum. Melalui pendekatan yang menggabungkan prinsip Rights, Restrictions, Responsibilities (RRRs), Funaya mampu mempertahankan identitas budaya sambil tetap mendorong keberlanjutan lingkungan dan ekonomi berbasis ekowisata. Model ini menunjukkan bahwa perlindungan budaya dan lingkungan tidak hanya mungkin berjalan berdampingan, tetapi juga dapat saling memperkuat, jika dirancang dengan regulasi yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan.
Zonasi, Hak, dan Harapan Baru untuk Suku Bajo
Melihat keberhasilan model Funaya di Jepang dalam menjaga kelestarian komunitas pesisirnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadaptasi pendekatan serupa dalam melindungi ruang hidup Suku Bajo. Adaptasi ini menjadi semakin penting mengingat berbagai tantangan yang kini mengancam keberlangsungan hidup Suku Bajo. Oleh karena itu, diperlukan kerangka perlindungan yang tidak hanya mengakui keberadaan Suku Bajo, tetapi juga berpihak pada hak-hak mereka sebagai masyarakat adat, dengan memperkuat peran mereka dalam mengelola ruang hidupnya sendiri secara berkelanjutan.
Kerangka perlindungan ini bertumpu pada prinsip Rights, Restrictions, Responsibilities (RRRs), sebuah pendekatan yang menggabungkan pengakuan hak, pembatasan penggunaan sumber daya untuk menjaga kelestarian, serta pembagian tanggung jawab antara komunitas dan pemerintah. Dalam penerapannya, ruang hidup Suku Bajo dirancang lewat sistem zonasi adaptif, di mana setiap kawasan memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung. Terdapat kawasan konservasi yang dikhususkan untuk perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, kawasan rawan bencana yang dilengkapi dengan infrastruktur mitigasi, hingga kawasan aktivitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat Bajo untuk mengelola sumber daya lautnya secara tradisional. Selain itu, disiapkan pula kawasan eksklusif yang hanya dapat diakses dan dikelola oleh komunitas Bajo sendiri, serta kawasan terbuka yang digunakan untuk kebutuhan umum seperti jalur transportasi laut dan kegiatan perikanan berkelanjutan.
Dalam kerangka ini, hak-hak Suku Bajo diakui secara penuh. Mereka berhak mengakses dan mengelola sumber daya laut secara tradisional, memperoleh perlindungan atas identitas budaya mereka, serta bermukim secara sah di wilayah perairan yang telah mereka tempati secara turun-temurun. Namun pengakuan hak ini juga disertai tanggung jawab yang besar. Suku Bajo diharapkan aktif menjaga kelestarian lingkungan mereka, mempertahankan kearifan lokal, serta berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menyediakan dukungan hukum, memperkuat infrastruktur adaptif, serta membangun sistem yang menjamin keberlangsungan ruang hidup mereka. Dengan sinergi ini, bukan tidak mungkin ruang hidup Suku Bajo bisa menjadi contoh pengelolaan pesisir yang adil, adaptif, dan berkelanjutan bagi komunitas adat lain di Indonesia.
Ketidakpastian Kebijakan dalam Upaya Melindungi Suku Bajo
Meskipun kerangka perlindungan berbasis prinsip Rights, Restrictions, Responsibilities (RRRs) menawarkan harapan baru bagi keberlangsungan hidup Suku Bajo, implementasinya di lapangan tidaklah mudah. Salah satu hambatan utama adalah birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih regulasi antara pengelolaan sumber daya sambil menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga program-program yang seharusnya mendukung komunitas pesisir justru terhambat atau tidak tepat sasaran.
Selain itu, minimnya dukungan infrastruktur di wilayah-wilayah tempat Suku Bajo bermukim menjadi tantangan tersendiri. Akses terbatas terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi laut yang memadai menghambat upaya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya mereka. Kondisi ini diperparah dengan adanya tekanan dari pembangunan pesisir yang tidak selalu mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan komunitas lokal.
Suku Bajo tidak hanya layak dilindungi, tetapi juga diberdayakan. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah pendataan kewarganegaraan berbasis komunitas, khususnya di wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil. Hal ini perlu didukung dengan program mobile service seperti akta lahir keliling dan dokumen identitas bergerak, agar masyarakat nomaden laut bisa mengakses status hukum tanpa harus berpindah ke daratan. Di sisi lain, pendidikan berbasis budaya laut juga penting untuk memastikan bahwa generasi muda Bajo tetap terhubung dengan identitasnya, sekaligus mendapatkan hak dasar sebagai warga negara. Terakhir, negara perlu mengakui secara hukum hak hidup komunitas laut sebagai bagian sah dari kekayaan kebangsaan, bukan sekadar “pendatang” di wilayah pesisir.
#MCPRDailyNews