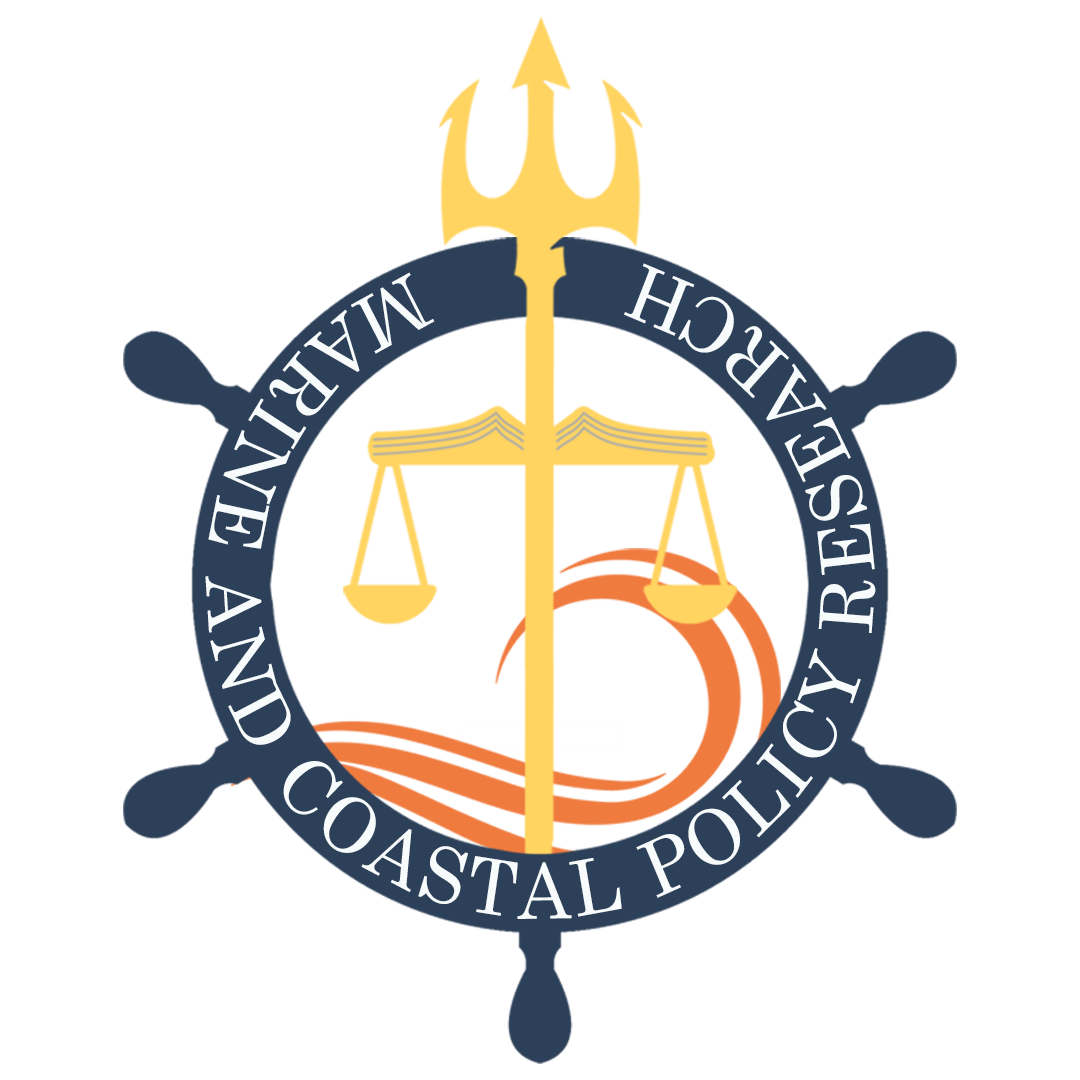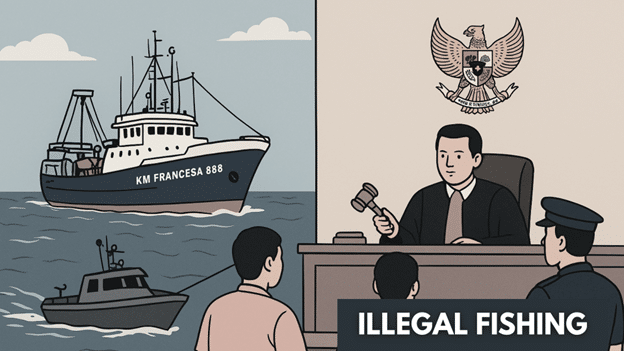Sumber : https://app.pandooin.com/blog/article/Rekomendasi-Wisata-Kepulauan-Seribu-untuk-Keluarga
Kawasan konservasi memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir sekaligus menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap target global, seperti Aichi target 11 dan SDGs target 14, dengan menetapkan 28,4 juta hektar perairan sebagai kawasan konservasi hingga 2021 dan menargetkan 35,2 juta hektar dari luas perairan pada 2030. Namun, kebijakan terbaru justru membuka peluang perubahan fungsi zona inti kawasan konservasi untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional, yang berpotensi melemahkan perlindungan ekosistem laut dan memberi legitimasi eksploitasi skala besar. Padahal, riset telah menunjukkan perubahan zona inti dapat menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Sementara pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia sendiri masih minim, dengan hanya 14% kawasan yang terkelola secara efektif. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara ambisi pembangunan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan laut.
Skenario Perubahan Zona Inti Kawasan Konservasi
Skenario implikasi perubahan status zona inti Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) umumnya disusun dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, potensi pengembangan, permasalahan pembangunan, serta tujuan Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, PSN dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa selain membawa dampak positif, PSN juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan berskala masif yang berdampak pada sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Dalam konteks pembangunan nasional, perubahan zona inti diarahkan untuk mendukung percepatan investasi dan target pertumbuhan ekonomi, seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 yang menargetkan pertumbuhan 6% dalam 5 tahun. Di sisi lain, pembangunan tersebut dapat menimbulkan tekanan signifikan terhadap ekosistem pesisir dan laut, khususnya terkait penurunan kualitas sumber daya lingkungan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 menegaskan bahwa zona inti sejatinya diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi pesisir, dengan pemanfaatan terbatas untuk penelitian. Perubahan fungsi zona inti hanya dapat dilakukan dalam rangka kebijakan nasional seperti PSN. Hal ini menimbulkan dilema, sebab meskipun pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, potensi degradasi ekosistem tetap tinggi. Selain pembangunan infrastruktur, sektor pariwisata juga dipandang sebagai pendorong utama dalam skenario perubahan zona inti. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 menekankan bahwa pengaturan kawasan konservasi tidak hanya berfokus pada alokasi lokasi perlindungan, tetapi juga pada pengelolaan objek konservasi. Pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan regulasi, serta penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek ekologi dan sosial. Selanjutnya, skenario masa depan perubahan zona inti harus mencakup dua arah utama, yaitu pembangunan infrastruktur dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi, serta alternatif skenario konservatif yang mempertahankan perlindungan zona inti tanpa intervensi kebijakan.
Tiga Skenario Masa Depan Zona Inti
Skenario A menekankan bahwa zona inti tetap dipertahankan sesuai fungsi awalnya tanpa perubahan signifikan. Kondisi ini memungkinkan perkembangan ekologi, ekonomi, dan sosial berlangsung secara alami. Dari sisi ekonomi, fokus diberikan pada pertumbuhan sektor informal, PDRB, dan pendapatan negara bukan pajak, sementara aspek sosial mencakup pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, serta pendidikan masyarakat pesisir.
Skenario B mengarahkan zona inti untuk pengembangan ekowisata dengan konsep keberlanjutan. Dalam pendekatan ini, kelestarian ekosistem pesisir, kualitas air, dan konservasi mangrove tetap dijaga sembari mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Pembangunan diarahkan pada sarana-prasarana wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Ekowisata dipandang mampu menghadirkan keseimbangan antara konservasi, peningkatan ekonomi lokal, dan kesejahteraan sosial.
Skenario C memposisikan zona inti sebagai ruang untuk percepatan pembangunan ekonomi, sejalan dengan kebijakan Proyek Strategis Nasional. Fokus utamanya adalah investasi pada infrastruktur, energi, industri, pertanian, kelautan, dan pariwisata. Pendekatan ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, namun memiliki risiko besar terhadap degradasi lingkungan pesisir dan laut jika tidak diimbangi dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
Perbandingan Tiga Skenario Zona Inti
Hasil analisis menunjukkan bahwa skenario A, yakni mempertahankan zona inti tanpa perubahan, memberikan nilai paling tinggi dari sisi ekologi. Indikator seperti kualitas air, luasan padang lamun, kondisi terumbu karang, hutan mangrove, hingga konservasi penyu berada dalam kondisi yang baik. Namun, skenario ini tidak menunjukkan peningkatan berarti, bahkan relatif lebih rendah bagi aspek ekonomi dan sosial. Meski begitu, secara regulasi skenario A tetap kuat, karena tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi konservasi dan sesuai dengan prinsip status quo.
Sebaliknya, skenario C yang membuka zona inti untuk kepentingan ekonomi memberikan keuntungan besar pada aspek sosial-ekonomi, terutama peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor informal. Akan tetapi, skenario ini membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan ekologi karena mengorbankan fungsi konservasi, serta dinilai lemah dari sisi regulasi. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off tajam antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan ekosistem pesisir jangka panjang.
Skenario B yang memanfaatkan zona inti untuk ekowisata memperlihatkan tren yang lebih seimbang. Nilai positif tidak hanya muncul pada aspek ekonomi dan sosial melalui peningkatan pendapatan masyarakat lokal, Produk Domestik Regional Bruto, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Secara regulasi, skenario ini berada pada posisi sedang, karena meskipun ada perubahan pada kawasan konservasi, ekowisata tetap mengedepankan asas keberlanjutan.
Berdasarkan perbandingan ketiga skenario, alternatif terbaik adalah skenario B. Opsi ini mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pariwisata berkelanjutan. Skenario A tetap relevan sebagai opsi kedua dengan fokus pada perlindungan ekologi, meskipun tidak memberi banyak dampak ekonomi. Sementara itu, skenario C dipandang sebagai pilihan terakhir karena meskipun menguntungkan secara ekonomi, berpotensi merusak fungsi ekologi dan bertentangan dengan arah kebijakan konservasi.
Writer : Marine and Coastal Policy Research Bureau