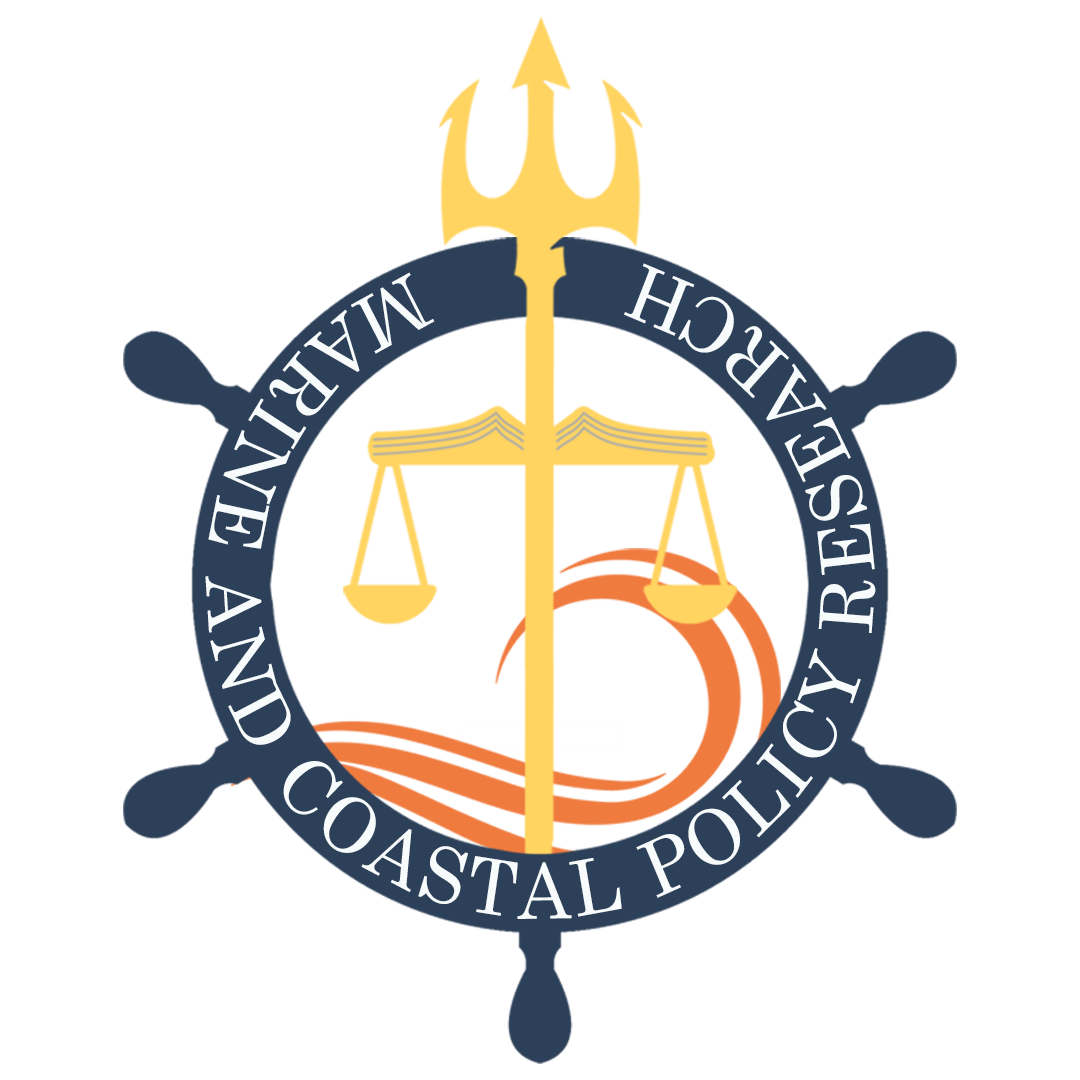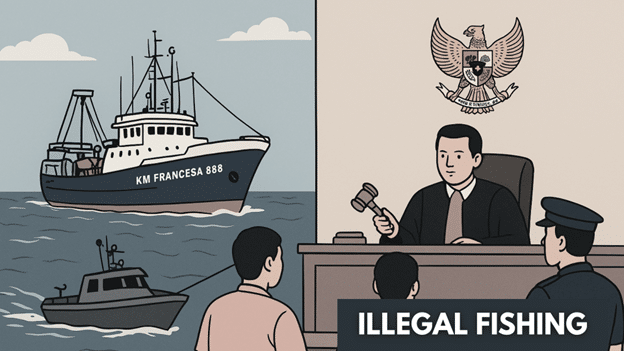Sumber :
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jmr/article/download/40428/31164
Kawasan pesisir merupakan wilayah transisi antara daratan dan lautan yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Pesisir menjadi lokasi pemukiman padat penduduk, kawasan industri, hingga daerah wisata, sehingga dinamika garis pantai berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Namun, garis pantai adalah fitur geomorfologi yang sangat dinamis dan rentan terhadap perubahan akibat proses alamiah seperti gelombang, pasang surut, badai, serta fenomena global seperti sea level rise (SLR). Aktivitas manusia, seperti pembangunan pelabuhan, konstruksi pantai, dan reklamasi, juga mempercepat perubahan garis pantai.
Indonesia dan Sri Lanka dipilih sebagai studi kasus karena keduanya sama-sama negara kepulauan yang terletak di wilayah tropis, rentan terhadap abrasi dan akresi, serta pernah terdampak bencana besar seperti tsunami 2004. Oleh karena itu, memahami pola perubahan garis pantai di kedua negara ini dapat memberikan gambaran penting untuk pengelolaan pesisir yang lebih berkelanjutan.
Perubahan Garis Pantai di Sri Lanka
Studi yang dilakukan oleh Nijamir et al. (2023) di Ampara District, Sri Lanka menganalisis perubahan garis pantai periode 1991–2021 dengan membagi wilayah kajian menjadi tiga desa: Nintavur, Oluvil, dan Palamunai. Data yang digunakan berupa citra satelit Google Earth dan Landsat, lalu diolah dengan Digital Shoreline Analysis System (DSAS) menggunakan variabel statistik seperti Net Shoreline Movement (NSM), End Point Rate (EPR), dan Linear Regression Rate (LRR).
Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah sekitar pelabuhan Oluvil mengalami erosi terparah, dengan nilai NSM mencapai -300,3 m/tahun di beberapa titik. Kondisi ini semakin jelas setelah pembangunan pelabuhan pada tahun 2008 yang mempercepat proses abrasi di bagian utara, sementara bagian selatan justru mengalami akresi. Prediksi untuk tahun 2031 memperkirakan erosi dan akresi masing-masing sebesar 61,4 ha dan 33,4 ha, sedangkan pada 2041 meningkat menjadi 81,7 ha dan 44,9 ha.
Dampak ekologis yang terjadi cukup besar, seperti hilangnya lebih dari 3.000 pohon kelapa, berkurangnya stok ikan akibat kerusakan ekosistem pesisir, serta perubahan pola sedimentasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pesisir tanpa pengelolaan yang tepat dapat mempercepat kerentanan garis pantai.
Perubahan Garis Pantai di Indonesia (Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)
Penelitian yang dilakukan oleh Dede et al. (2023) mengambil studi kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data Landsat (1981–2021) dan garis pangkal dari peta Hindia Belanda 1945. Penelitian ini lebih komprehensif karena tidak hanya menggunakan variabel statistik (EPR, LRR, NSM, SCE), tetapi juga variabel fisik seperti kedalaman laut, slope dasar laut, kecepatan angin, Total Suspended Solid (TSS), jarak estuari sungai, dan keberadaan konstruksi pantai.
Hasil menunjukkan bahwa garis pantai di Bengkayang sangat dinamis. Akresi terjadi pada tahun 1981, 1991, dan 2021, yang banyak dimanfaatkan sebagai kawasan mangrove atau lahan garam. Sebaliknya, abrasi dominan terjadi pada tahun 2001 dan 2011. Wilayah paling dinamis adalah segmen 8 yang mengalami siklus akresi–abrasi–akresi tiap dekade, sedangkan segmen 1 dan 5 relatif stabil.
Prediksi hingga tahun 2031 dan 2041 memperkirakan adanya abrasi signifikan yang dapat mengurangi daratan hingga 244,04 m, namun di sisi lain juga berpotensi terjadi akresi yang menambah daratan sekitar 217,60 m. Hal ini memperlihatkan dinamika pesisir yang sangat kompleks, di mana perubahan garis pantai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor global tetapi juga faktor lokal.
Faktor Penyebab dan Dampak Sosial-Ekonomi
Faktor penyebab perubahan garis pantai di kedua negara memiliki karakteristik yang berbeda. Di Sri Lanka, penyebab utama adalah pembangunan pelabuhan, terutama di kawasan Oluvil, yang menimbulkan ketidakseimbangan distribusi sedimen di sekitar pantai. Kondisi ini diperparah oleh faktor iklim dan bencana alam seperti badai siklon, banjir rob, serta tsunami yang semakin mempercepat proses erosi. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut antara lain hilangnya vegetasi pesisir, kerusakan pada lahan pertanian, serta penurunan hasil tangkapan ikan yang merugikan nelayan setempat. Sementara itu, di Indonesia khususnya di
Kabupaten Bengkayang, perubahan garis pantai lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti kedalaman laut yang dangkal, arus laut, proses sedimentasi, serta keberadaan konstruksi pantai. Aktivitas manusia berupa pertumbuhan permukiman di wilayah pesisir juga ikut mempercepat dinamika perubahan garis pantai. Dampak yang ditimbulkan mencakup konversi lahan pertanian, ancaman terhadap aktivitas nelayan, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Namun berbeda dengan di Sri Lanka, pembangunan konstruksi pantai di Bengkayang justru dapat memberikan dampak positif, karena mampu memperkuat garis pantai dan menahan laju abrasi di beberapa wilayah.
Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir
Perubahan garis pantai memiliki implikasi besar terhadap kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Di Indonesia, garis pantai menjadi dasar penting dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) karena luas wilayah laut dihitung dari garis pantai. Perubahan garis pantai akan mempengaruhi besarnya anggaran yang diterima daerah. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki instrumen hukum berupa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang berlaku selama 20 tahun sebagai acuan tata ruang laut.
Diperlukan langkah mitigasi berbasis ekosistem seperti rehabilitasi mangrove, pembangunan sabuk pantai, serta pengawasan berkala dengan teknologi penginderaan jauh. Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur pesisir harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang.
Writer : Land-Sea Dynamic Bureau